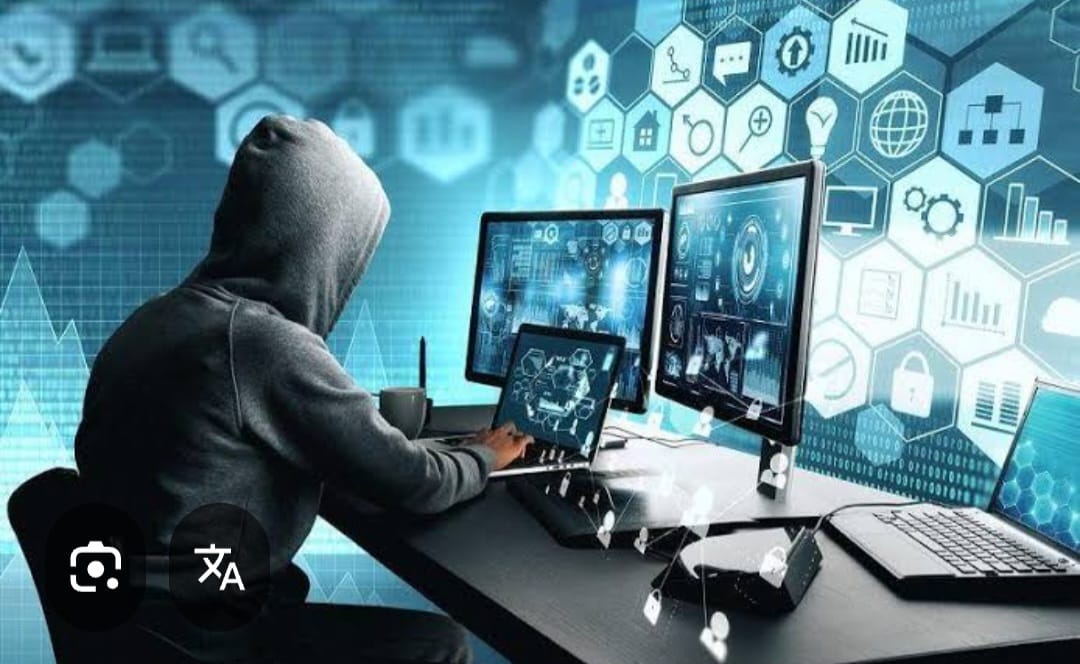Pertanyaannya: mampukah hukum kita beradaptasi dan bertransformasi secepat kemajuan teknologi yang pelaku miliki untuk menciptakan teror virtual?
Dalam teori hukum Jerman ada dua konsep penting yang menarik untuk dilihat, Das Sollen (yang seharusnya) dan Das Sein (yang terjadi). Dua konsep ini menjadi cermin bagi hukum siber Indonesia. Secara de jure (das Sollen), perangkat hukum kita tampak lengkap mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hingga kebijakan keamanan siber nasional. Namun secara _de facto_ _(das Sein), penegakan hukum masih jauh tertinggal dari dinamika dunia digital yang tanpa batas dan berlapis teknologi anonimitas.
Kasus ancaman bom melalui digital attack di tiga sekolah internasional menunjukkan bahwa pelaku mampu bersembunyi di balik alamat email acak, nomor internasional, dan transaksi kripto yang sulit dilacak. Semua berada di luar jangkauan yurisdiksi hukum nasional. Penegakan hukum menjadi terasa lamban karena terbatasnya kemampuan sumber daya digital forensik yang kita miliki, minimnya kerja sama internasional, serta belum adanya mekanisme hukum yang adaptif dalam menghadapi kejahatan siber lintas yurisdiksi. Inilah jurang antara hukum yang ideal dan realitas lapangan, antara teks undang-undang dan dunia digital yang terus berubah.
Masalah utama kita bukan pada ketiadaan aturan, tetapi pada ketimpangan antara hukum dan sumber daya manusia penegak hukumnya. Idealnya, aparat hukum dibekali dengan kemampuan teknologi mutakhir, jaringan kerja internasional, dan sistem koordinasi lintas lembaga yang efisien. Namun faktanya, koordinasi antara lembaga yang ada, baik BNPT, Polri, dan Kominfo masih sering tumpang tindih, birokrasi berjalan lambat, dan belum terintegrasi secara digital. Sementara para pelaku baik teroris maupun penipu siber semakin canggih memanfaatkan kecerdasan buatan AI (Artificial Intelligent), deepfake, dan phishing berbasis ideologis untuk menipu publik.